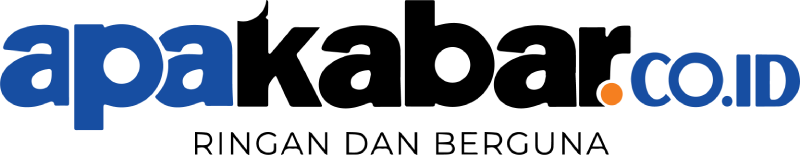OPINI
Jejak Deforestasi dan Tantangan Ekonomi Hijau pada Bencana di Sumatera

Oleh: Misbakhul Munir*
Banjir dan longsor besar yang melanda Sumatera pada akhir November hingga awal Desember 2025 kembali menegaskan kerentanan ekologis Indonesia. Peristiwa ini bukan semata hasil dinamika alam, tetapi merupakan akumulasi panjang kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia.
Deforestasi masif, drainase gambut, dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali menjadi pemicu utama melemahnya daya dukung hidrologi di Pulau Sumatera. Ketika hujan ekstrem datang, ekosistem yang telah rusak tidak mampu menahan limpasan air, sehingga banjir bandang dan longsor terjadi hampir bersamaan di berbagai daerah.
Laju deforestasi dua dekade terakhir merupakan faktor paling signifikan dalam menjelaskan kerentanan wilayah terdampak. Pemantauan tutupan lahan menggunakan citra satelit, seperti laporan Global Forest Watch dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), mengindikasikan bahwa Sumatera kehilangan jutaan hektare hutan alam sejak awal 2000-an.
Hilangnya hutan akibat ekspansi sawit, kehutanan industri, dan pembangunan infrastruktur membuat fungsi hidrologis kawasan hulu rusak. Sejumlah penelitian hidrologi menunjukkan bahwa deforestasi meningkatkan rasio aliran permukaan (runoff), menurunkan infiltrasi, dan mempercepat erosi.
Kondisi ini mengakibatkan daerah aliran sungai (DAS) merespons hujan ekstrem dengan lebih cepat, menyebabkan kenaikan debit sungai yang tajam dalam waktu singkat. Daerah-daerah rusak paling besar dalam bencana 2025 memiliki riwayat kehilangan tutupan hutan yang tinggi, menguatkan hubungan kausal antara degradasi lahan dan tingginya risiko banjir.
Kerusakan gambut memperburuk risiko, khususnya di dataran rendah Sumatera. Secara ekologis, lahan gambut berfungsi sebagai reservoir air alami. Namun drainase untuk membuka perkebunan sawit dan hutan tanaman industri telah membuat muka air gambut turun drastis sehingga permukaan tanah turun dan kehilangan kapasitas tampung air.
Berbagai studi internasional di jurnal Wetlands Ecology and Management, Forest Ecology and Management, serta publikasi MDPI menunjukkan bahwa gambut yang dikeringkan dapat kehilangan hingga 80 persen kemampuan retensi air.
Ketika hujan ekstrem tiba, air tidak lagi diserap tetapi mengalir deras ke hilir, menciptakan banjir bandang. Penelitian lapangan di Riau dan Sumatera Selatan juga menemukan hubungan kuat antara kepadatan kanal drainase, penurunan permukaan gambut, dan frekuensi banjir bandang.
Selain bukti ekologis, pemodelan hidrologi menggunakan simulasi 1D/2D pada sungai-sungai besar di Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Barat telah mengonfirmasi kerusakan kapasitas tampung sungai. Sedimentasi tinggi, perubahan geometri alur sungai, dan menurunnya roughness membuat sungai lebih cepat meluap.
Debit puncak muncul dalam durasi yang lebih singkat sehingga banjir bersifat bandang dan memberikan sedikit waktu bagi warga untuk menyelamatkan diri. Kerusakan ini memperlihatkan bagaimana degradasi ekosistem di hulu, tengah, dan hilir bekerja secara simultan menghasilkan bencana berskala besar. Dampak bencana pada tahun 2025 menunjukkan skala kerusakan yang luar biasa.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 6 Desember 2025, tercatat 883 orang meninggal, 520 orang hilang, dan sekitar 4.200 warga mengalami luka-luka, menjadikannya salah satu bencana paling mematikan satu dekade terakhir.
Lebih dari 121.000 rumah rusak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Infrastruktur vital, seperti sekolah, pusat kesehatan, jembatan, hingga jaringan transportasi, juga hancur sehingga menyulitkan distribusi bantuan.
Selain banjir, paparan asap dari kebakaran gambut yang terjadi secara berkala memperparah kondisi kesehatan masyarakat setelah bencana. Semua ini menguatkan alasan para peneliti untuk menggolongkan peristiwa ini sebagai artificial man-made disaster, yakni bencana yang diperparah atau bahkan disebabkan oleh aktivitas manusia.
Penyebab utama bencana ini bersumber dari pengabaian terhadap batas daya dukung lingkungan. Deforestasi, konversi gambut, dan pembangunan yang tidak mempertimbangkan risiko ekologis telah mempersempit ruang air untuk mengalir dan meresap.
Ketika perubahan iklim meningkatkan frekuensi hujan ekstrem, sistem ekologis yang telah rusak tidak mampu lagi menjadi pelindung alami. Hujan ekstrem hanyalah pemicu; kerentanan tercipta oleh aktivitas manusia selama puluhan tahun.
Oleh karena itu, pemulihan ekosistem harus menjadi prioritas utama. Restorasi gambut melalui penutupan kanal, rewetting, dan pengendalian kebakaran diperlukan untuk memulihkan fungsi hidrologis.
Rewetting, membasahi kembali lahan gambut, terbukti mengurangi risiko kebakaran hingga 70 persen dan meningkatkan kapasitas tampung air gambut secara bertahap, sebagaimana dilaporkan oleh studi-studi di Nature Climate Change dan Environmental Research Letters.
Di kawasan hulu DAS, rehabilitasi hutan dapat menurunkan runoff, memperbaiki infiltrasi, dan mengurangi erosi. Tata ruang berbasis risiko juga harus diterapkan secara ketat untuk melarang pembangunan di zona rawan dan melindungi koridor sungai.
Namun upaya pemulihan lingkungan tidak terlepas dari tantangan besar, terutama dalam konteks transisi menuju ekonomi hijau. Struktur ekonomi Sumatera yang sangat bergantung pada sektor ekstraktif seperti sawit, batu bara, dan industri berbasis lahan menjadikan perubahan menuju praktik berkelanjutan menghadapi resistensi sosial.
Masyarakat lokal memerlukan alternatif pendapatan yang layak melalui agroforestry, pertanian regeneratif, ekowisata, dan inovasi ekonomi lainnya. Transisi ini membutuhkan dukungan modal, pelatihan, dan insentif yang memadai.
Selain itu, pendanaan internasional untuk iklim seringkali lambat dan penuh syarat, sehingga green bonds, pembayaran jasa lingkungan, dan transfer teknologi harus diperkuat untuk menunjang transisi energi bersih dan pembangunan berkelanjutan.
Penegakan hukum juga menjadi tantangan besar. Banyak kasus deforestasi dan alih fungsi lahan berlangsung melalui celah perizinan atau lemahnya pengawasan. Tanpa transparansi dan pengendalian ketat, berbagai program restorasi dan ekonomi hijau akan sulit mencapai target.
Peristiwa banjir Sumatera 2025 memberi pelajaran bahwa arah pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari keberlanjutan ekologis. Bencana ini menunjukkan bahwa manusia bukan hanya korban, tetapi juga pencipta risiko. Namun manusia pula yang memegang kunci solusi.
Jika pengalaman ekologis ini menjadi dasar kebijakan publik dan arah pembangunan, Sumatera dan seluruh Indonesia memiliki peluang membangun masa depan yang lebih aman, berketahanan, dan ekologis.
Banjir 2025 harus menjadi titik balik: Apakah bangsa ini siap meninggalkan pola lama yang merusak dan melangkah menuju pembangunan yang adil, lestari, dan berjangka panjang, atau kembali pada pola yang menciptakan bencana serupa di masa depan.
*) Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya
Editor:
BETHRIQ KINDY ARRAZY
BETHRIQ KINDY ARRAZY