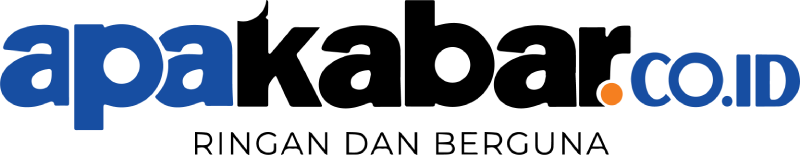OPINI
Lingkaran Setan Bencana Banjir Sumatera

Oleh: Rimun Wibowo*
Bencana banjir dan longsor di Sumatera kembali menegaskan bahwa Indonesia masih menghadapi kegagalan struktural dalam mengelola sumber daya alam.
Peristiwa tersebut sering disederhanakan sebagai musibah alam atau dampak hujan ekstrem, padahal secara ilmiah bencana tersebut merupakan akumulasi dari deforestasi, tata kelola yang lemah, dan pengabaian prinsip environmental & social governance (ESG) dalam investasi dan pembangunan.
Banjir di Sumatera bukanlah fenomena tunggal, tetapi puncak dari rantai sebab akibat yang dimulai dari kebijakan ekonomi-politik, diikuti eksploitasi sumber daya alam, tanpa perlindungan, dan diakhiri dengan kerentanan sosial masyarakat.
Infrastruktur Ekologis
Dalam perspektif lingkungan, hutan tropis adalah infrastruktur ekologis yang berfungsi sebagai penyerap dan penyimpan air hujan dan pengikat tanah untuk pencegahan longsor. Hutan tropis juga menjadi infrastruktur pengatur debit aliran sungai dan berperan sebagai penopang keanekaragaman hayati serta sistem sosial setempat.
Hanya saja, fungsi ekologis tersebut terpinggirkan ketika kebijakan pembangunan lebih mengutamakan optimalisasi komoditas ekonomi dibanding daya dukung lingkungan.
Pemberian konsesi lahan untuk perkebunan, pertambangan, dan proyek besar dilakukan tanpa penilaian risiko lingkungan–sosial yang memadai dan tanpa mekanisme pengawasan independen. Akibatnya, kapasitas alam dalam mengendalikan risiko banjir menurun signifikan.
Ekonomi Politik
Pendapatan dari sektor ekstraktif memang berkontribusi pada ekonomi nasional dan daerah. Namun dalam kenyataan di lapangan, arus keuntungan lebih dominan mengalir ke elite ekonomi dan politik, bukan ke masyarakat di wilayah terdampak.
Pola ekonomi politik yang berulang dapat diringkas sebagai berikut: korporasi memperoleh izin konsesi untuk membuka hutan; keuntungan ekonomi terkonsentrasi di aktor-aktor kuat melalui aliansi bisnis–politik; kebijakan publik cenderung pro-eksploitasi: regulasi longgar, pengawasan minim, dan pemberian izin berulang; risiko ekologis dialihkan ke masyarakat, sementara manfaat ekonomi terpusat pada kelompok kecil.
Dalam perspektif tata kelola, fenomena ini menunjukkan defisit good governance, terutama pada aspek transparansi, akuntabilitas, independensi pengawasan, serta partisipasi publik dalam pengambilan keputusan.
Absennya ESG
Di tingkat global, standar ESG mewajibkan bahwa investasi harus menjaga keberlanjutan ekologi, melindungi masyarakat terdampak, dan memastikan manfaat ekonomi yang inklusif.
Dalam kasus banjir Sumatera, absennya environmental & social safeguards (ESS) terlihat jelas. Tahap-tahap mitigasi risiko yang seharusnya ada, yang meliputi identifikasi dampak, konsultasi publik, penilaian risiko, rencana perlindungan sosial–lingkungan, dan monitoring independen, tidak dijalankan secara memadai.
Ketika perlindungan tersebut tidak diterapkan, dampaknya adalah deforestasi yang berlangsung cepat, daerah aliran sungai (DAS) yang rusak parah, dan tutupan tanah yang makin hilang. Dampak lain adalah meningkatnya aliran permukaan, sehingga permukiman dan infrastruktur menjadi rentan.
https://apakabar.co.id/opini/jejak-deforestasi-dan-tantangan-ekonomi-hijau-pada-bencana-di-sumatera/
Hujan ekstrem hanya mempercepat konsekuensi yang sudah tercipta. Dalam situasi seperti ini, mereka yang paling tidak menikmati keuntungan ekonomi justru menjadi pihak yang paling menanggung risiko bencana. Masyarakat kehilangan rumah dan aset produktif, akses ekonomi dan pendidikan terputus, serta muncul kerentanan kesehatan dan sosial yang berkepanjangan.
Tanpa perlindungan sosial berbasis mitigasi risiko, masyarakat akan terus menjadi korban dari kebijakan eksploitasi yang tidak berkelanjutan.
Siklus Berulang
Bencana tidak langsung menghasilkan reformasi kebijakan. Sebaliknya, terdapat mekanisme siklus sosial–politik yang mengunci situasi.
Ketika bencana terjadi, warga menjadi pihak yang paling menderita. Bantuan darurat memang segera hadir, namun ini tidak mengubah sistem tata kelola.
Dalam kondisi demikian, kemudian muncul narasi politis yang dimanfaatkan untuk menarik empati publik menjelang pemilu. Ujung-ujungnya, pilihan politik tidak berubah, sehingga kebijakan pun juga tidak berubah.
Konsesi baru tetap diberikan dan kerusakan lingkungan berulang. Bencana berikutnya hanya soal waktu. Krisisnya bukan hanya lingkungan, tetapi governance.
Peristiwa banjir dan longsor di Sumatera pada akhir November hingga awal Desember 2025 menegaskan betapa rapuhnya tata kelola sumber daya alam Indonesia. BNPB mencatat 836 korban jiwa dan lebih dari setengah juta mengungsi, menjadikan bencana ini salah satu yang paling mematikan dalam satu dekade terakhir.
Kerusakan terbesar terjadi di Aceh Tamiang, Tapanuli Utara, dan Agam, di mana akses jalan terputus total dan ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal.
Banjir Sumatera adalah konsekuensi dari tata kelola sumber daya alam yang tidak adaptif dan tidak akuntabel serta investasi yang mengabaikan prinsip-prinsip ESG. Bencana ini juga merupakan akibat dari absennya penerapan perlindungan lingkungan dan sosial serta lemahnya kontrol publik terhadap kebijakan eksploitasi.
Selama sistem perizinan dan pengelolaan tidak berbasis risk governance dan tidak memprioritaskan keberlanjutan ekologi dan keadilan sosial, maka bencana serupa akan terus berulang.
Untuk keluar dari lingkaran ini, pemerintah, korporasi, dan masyarakat perlu mendorong integrasi ESG dalam seluruh proses investasi dan perizinan.
Ke depan, environmental & social safeguards (ESS) berbasis standar internasional wajib diterapkan, bukan sekadar administrasi dokumen.
Transparansi dan akuntabilitas tata kelola menjadi hal krusial untuk dijaga melalui pengawasan independen. Perlu ada keterlibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dan monitoring lingkungan.
Sanksi tegas perlu ditegakkan atas pelanggaran tata kelola, termasuk pencabutan izin yang menyebabkan kerusakan ekologi.
Dengan tata kelola yang baik, pembangunan tidak harus bertentangan dengan kelestarian ekologi. Bencana banjir bukan keniscayaan — ia dapat dicegah jika tata kelola, ESG, dan perlindungan atau keamanan dijalankan secara konsisten.
*) Dosen Ilmu Lingkungan dan Wakil Dekan Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Ibn Khaldun Bogor
Editor:
BETHRIQ KINDY ARRAZY
BETHRIQ KINDY ARRAZY